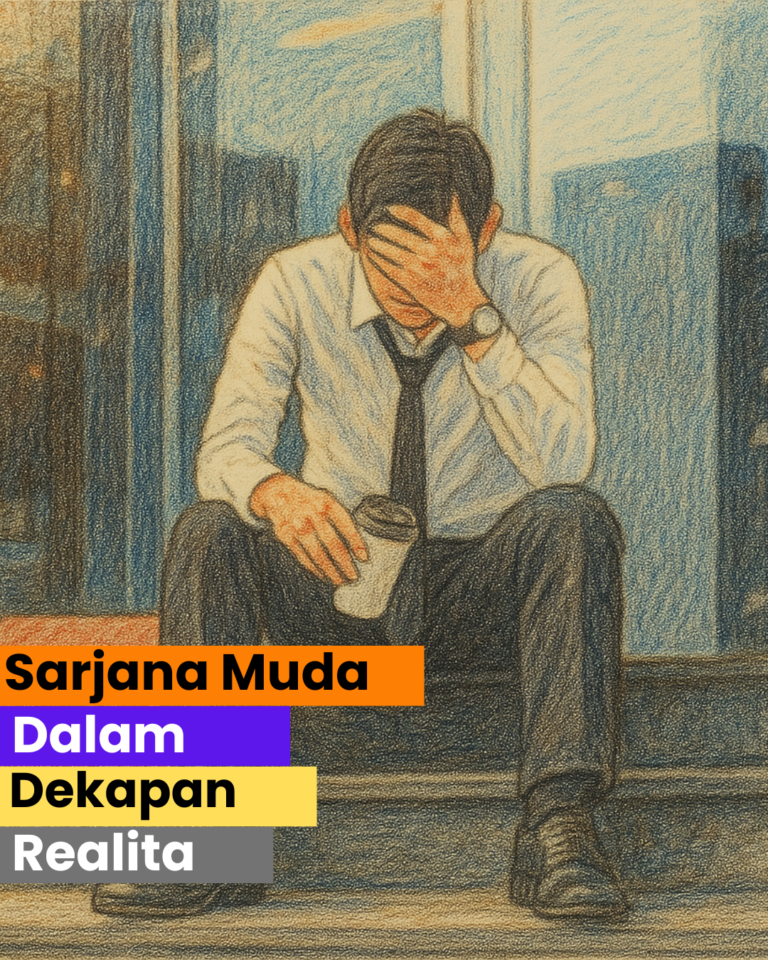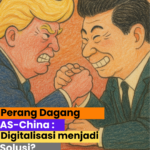Menjadi sarjana adalah sebuah hal yang Istimewa bagi sebagian orang. Dianggap punya ilmu diatas rata-rata, memiliki harapan kerja di ruangan ber ac perkantoran, dan juga dianggap punya previllage lebih ditengah masyarakat. Namun, Identitas gelar sarjana ini juga menjadi beban moral yang terus menghantui seorang sarjana.
Dalam pusara realita banyak sarjana muda yang terjebak dalam identitas kesarjanaannya. Dihadapkan pada realita sulitnya mencari kerja sesuai jurusan. Seorang sarjana muda terkadang harus merelakan mimpinya demi bertahan hidup. Bekerja apapun akan dilakukan, sekalipun tidak sesuai jurusan dan ijazahnya tak terpakai terlantar sia-sia, yang penting bisa menyambung hidup.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka sarjana pengangguran terus menjadi sorotan. Pada 2014, tercatat ada 495.143 penganggur kategori lulusan universitas. Angka tersebut terus meroket hingga mencapai 981.203 pada 2020, angka ini akhirnya sedikit turun menjadi 842.378 pada 2024.
Hal ini seakan menjelaskan, meski pendidikan tinggi sering dianggap sebagai jalan untuk jaminan hidup yang lebih baik, realitanya tidak selalu demikian. Dalam rentang waktu 2014 sampai 2020, angka sarjana pengangguran meroket hampir dua kali lipat.
Pandemi Covid-19 pada 2020 menjadi salah satu penyebab terbesar, ketika dunia kerja lumpuh dan banyak perusahaan memberlakukan pembatasan rekrutmen. Meski pasca-pandemi angka ini mulai menurun, penurunan tersebut tidak cukup signifikan untuk menghapus bayang-bayang ancaman pengangguran sarjana.
Jika kita bandingkan dengan lulusan SMA (SLTA Umum), jumlah pengangguran pada kategori ini memang lebih besar secara absolut, yakni mencapai 2.513.481 pada 2023.
Namun, perlu diketahui. Tingkat kompetisi lapangan kerja kategori lulusan SMA cenderung berbeda. Banyak dari mereka yang masuk ke sektor informal atau pekerjaan dengan keahlian berbeda, di mana kualifikasi tinggi tidak selalu menjadi prioritas.
Sebaliknya, kategori alumni universitas sering kali terjebak dalam “aspirational mismatch,” yaitu kondisi di mana ekspektasi terhadap pekerjaan tidak sesuai dengan realitas yang tersedia di pasar kerja. Inilah salah satu sebab para sarjana lebih lama menganggur dibandingkan lulusan SMA atau bahkan lulusan diploma.
Lulusan akademi atau diploma, di sisi lain, menunjukkan tren yang lebih stabil dibandingkan sarjana. Pada 2014, jumlah penganggur dari kategori ini tercatat sebanyak 193.517 orang. Meski sempat meningkat menjadi 305.261 pada 2020, angka ini kembali turun ke 170.527 pada 2024. Stabilitas ini bisa dikaitkan dengan program pendidikan diploma yang lebih fokus pada keterampilan praktis dan kebutuhan industri.
Menjadi mahasiswa di era dunia saat ini, yang serba cepat. Yang seakan mengalihkan pendidikan di perguruan tinggi dari tempat belajar dan mendalami ilmu menjadi tempat persiapan kerja. Mahasiswa era sekarang seakan hanyalah sekedar mengejar gelar dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja. Bukan lagi tentang tridharma perguruan tinggi. Kita seakan kehilangan tridharma perguruan tinggi. Bahkan bukan hanya kehilangan tridharma, kita juga kehilangan arah akan masa depan bangsa. Para mahasiswa mulai jauh dari kepekaan sosial, kesadaran moral, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam tridharma perguruan tinggi.
Mengutip dari Variyaka Blog dalam artikelnya yang berjudul GELAR KESARJANAAN, ZAMAN DULU DAN SEKARANG …disana penulis menuturkan “Mengenai masalah ini, saya sempat Berdiskusi dengan Almarhum Profesor Soetandyo Wignyosoebroto, seorang guru besar di bidang Ilmu Sosial di Kampus tempat saya kuliah S3 beberapa tahun yang lalu. Mendengar penuturan beliau tentang masa kuliah S1 yang beliau jalankan dulu, terus terang saya sirkus alias iri, dan lebih dari itu, akhirnya saya tahu, apa yang membedakan seorang Drs atau Dra dengan S …, apapun di zaman sekarang.
Dahulu, untuk bisa menjadi sarjana penuh, yang sekarang kira-kira setingkat S1, seorang mahasiswa harus terlebih dahulu melewati jenjang Sarjana Muda dengan gelar B.Sc., BA, (“Belum Apa-apa”) :), yang diletakkan setelah nama. Dan, jangan pernah mengira bahwa mereka dengan gelar Drs atauDra itu simply setara dengan lulusan S1 sekarang. “Drs” merupakan gelar kesarjanaan warisan zaman Belanda yang merupakan singkatan dari “Doktorandus”.
Dengan demikian, seorang sarjana bergelar Drs (untuk laki-laki) atau Dra (untuk perempuan, singkatan dari “Doktoranda”) sebenarnya memiliki level pengetahuan dan kualitas akademis yang setingkat dengan lulusan S2, karena Doktorandus kurang lebih bermakna “Calon Doktor”.
Nah, sampai sini, apa yang kira-kira bisa kita simpulkan? Berarti S1 sekarang, sebenarnya setingkat dengan B.Sc. alias sarjana muda, atau belum sarjana full. Belum percaya? Coba di cek, apa bahasa Inggris dari skripsi yang tertera di transkrip nilai? Undergraduate Theses. Terimalah sebuah kenyataan yang menyedihkan itu saudara-saudara ��”
Bagaimana bisa kesenjangan kualitas pendidikan zaman dulu dan sekarang bisa begitu jauh? Sarjana zaman dulu punya kualitas yang tidak perlu diragukan lagi. Banyak tokoh-tokoh zaman dulu yang menjadi testimoninya. Sebut saja Bung Karno, Bung Hatta, Gus Dur, Bj. Habiebie, Sjahrir, Tan Malaka, dan masih banyak lagi.
Mengutip dalam artikel yang sama. Disana dituturkan “Kesuraman akademis ini sebenarnya berpangkal di zaman ORBA ketika Presiden kita saat itu, Alm. Pak Harto nan murah senyum itu, bersama dengan Menteri Pendidikannya (orang Madura, saya lupa siapa namanya), mempropagandakan Link & Match. Slogan ini juga merupakan arahan bagi kurikulum pendidikan kita yang dianggap perlu ditinjau ulang (baca: diacak-acak) untuk disesuaikan dengan tuntutan zaman menurut Pak Harto.
Saat itu, Pak Harto dan menterinya ini menghendaki agar masa kuliah mahasiswa di tiap jenjang dibatasi supaya proses penyerapan tenaga kerja di dunia usaha saat itu terjadi secara simultan. Dengan demikian, semua sarjana dari bidang apapun diharuskan menjadi tenaga siap kerja. Imbasnya, semua fakultas yang ada di semua perguruan tinggi diharuskan menyusun kurikulum untuk bisa menyesuaikan diri dengan regulasi ini.
Akibatnya, selain pembatasan masa studi mulai diberlakukan, mulai banyak pula mata kuliah yang dibatasi dan ditutup. Mata kuliah yang dipertahankan atau yang diadakan, diupayakan merupakan mata kuliah yang bersifat aplikatif dan punya kemampuan “terpakai” di ranah komersial. Dan, setelah berpuluh-puluh tahun berlalu, orientasi pendidikan di tingkat pendidikan tinggi semacam ini masih saja bertahan, bahkan menunjukkan tanda-tanda kian menguat.
Terbentuklah lingkaran komersial pendidikan tinggi imajiner : (masuk) Universitas kian mahal > masa studi dipersingkat > kuliah dipadatkan > tugas akhir dipermudah > masa lulus dipercepat > Jadi Penganggur. Jadi, universitas tidak mencetak sarjana yang pintar, dan mirisnya lagi, juga tidak mencetak tenaga kerja profesional. Sekarang, coba bayangkan saja, apa yang bisa diharapkan dari calon mahasiswa yang masuk kampus (baca: kuliah) dengan motivasi YAITU : Pertama, Cepat lulus; Kedua, Dapat kerja dengan posisi hebat dan gaji bagus”.
Pada kehidupan Era teknologi ini yang memdistrupsi tatanan manusia menjadi serba instan dan cepat. Membuat sebagian besar manusia menjadi semakin jauh dari pendalaman ilmu2 secara mendalam, bahkan semakin kehilangan arah dan jati dirinya. Tak terkecuali seorang sarjana. Banyak sarjana yang pada akhirnya harus mengubur mimpinya karena bekal yang diperoleh dalam proses S1 nya ternyata belum cukup untuk berkompetisi dalam dunia kerja professional. Ternyata masih banyak proses yang mesti dilalui lagi.
Namun, banyak sarjana yang memilih untuk berhenti melanjutkan studinya sebab terkendala masalah finansial. Karena mahalnya biaya studi lanjut untuk memenuhi syarat kompetensi sebelum terjun dalam dunia professional. Seperti contohnya seorang Sarjana Hukum, ia mesti melanjutkan studinya untuk beberapa bidang pekerjaan, seperti sekolah kenotariatan (Magister Kenotariatan) dengan biaya berkisar 11 Juta Rupiah per Semester, sekolah advokad (PKPA) dengan biaya sekitar 6 juta rupiah, dan lain lain. Hal ini sungguh ironi yang entah kapan akan terurai.
Finansial menjadi salah satu faktor dalam kumpulan faktor yang menjadi sebab seorang sarjana kehilangan arah hidupnya. Karena desakan kebutuhan, terkadang mahasiswa lebih memilih mementingkan kerja daripada belajar. Yang pada akhirnya pada saat lulus. Ilmu yang didapatkan saat kuliah tidak cukup untuk berkompetisi dalam persaingan mencari lapangan kerja sesuai bidang keilmuannya. Hingga kemudian merelakan ilmunya sia-sia, mengubur mimpinya, dan bekerja seadanya.